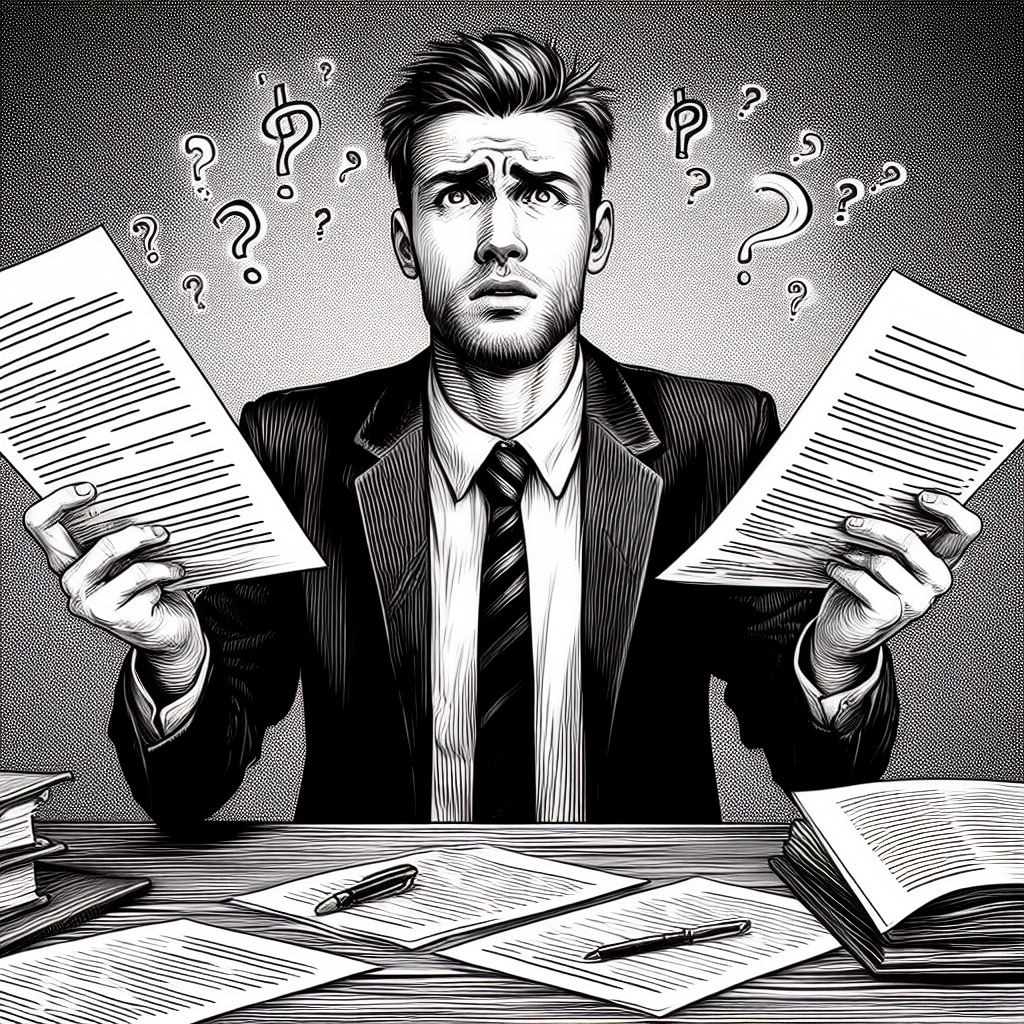Semenjak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tgl. 20 Juni 2013, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 12 Februari 2014dan Putusan Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015di mana Pengadilan berpendapat, bahwa pelanggaran atas Ps. 31 Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (“UU No. 24/2009”) adalah batal demi hukum, karena dianggap ada kausa yang terlarang. Permasalahan keabsahan perjanjian Bahasa asing terus menjadi perdebatan.
Pasal 31 UU No. 24/2009 mengatur:
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.
Apabila dilihat isi Pasal tersebut, ketentuan di atas berbicara secara umum tentang perjanjian, di mana salah satu pihaknya adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) atau lembaga swasta Indonesia dan pihak yang lainnya adalah orang asing ataupun kedua belah pihaknya adalah WNI atau lembaga swasta Indonesia.
Ketentuan dalam Pasal 31 UU No. 24/2009 ini kemudian Kembali dipertegasdalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres No.63/2019”) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019. Perpres ini memberikan ketentuan tambahan bahwa para pihak dapat menyepakati mengenai bahasa yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran. Namun, beberapa masalah masih belum jelas termasuk mengenai keabsahan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing di mana salah satu atau kedua belah pihaknya adalah WNI.
Mengingat Perpres No.63/2019 ini justru mempertegas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, dalam praktiknya ketentuan ini sering kali disalahgunakan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Suatu pihak dalam perjanjian, yang pada awalnya tidak pernah mempermasalahkan perjanjian yang ia tandatangani dalam bahasa asing, baru mempermasalahkan hal itu, ketika debitur berada dalam keadaan terjepit seperti ketika debitur tidak bisa memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik, ketika kreditnya macet dan menghadapi eksekusi jaminan, Debitor tersebut dapat mencari perlindungan di belakang ketentuan Pasal 31 UU No. 24/2009, dengan menuntut pembatalan perjanjian kredit, atas dasar perjanjian itu melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa.
Oleh karena itu, dalam praktiknya para pihak dalam perjanjian “wajib” untuk membuat perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing. Metode yang umum yaitu langsung membuat perjanjian dalam dua bahasa atau membuat perjanjian dalam bahasa asing kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
Rumusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Rujukan Penerapan Pasal 31 UU No. 24/2009
Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 (“SEMA 3/2023”), Kamar Perdata Mahkamah Agung memberikan suatu rumusan terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 ini, yaitu:
“Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.”
Rumusan ini mengubah paradigma dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang awalnya menganggap pelanggaran Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 sebagai kausa terlarang menjadi tetap sah selama tidak didasarkan iktikad buruk.
Rumusan Mahkamah Agung ini patut untuk disambut baik karena menegaskan penerapan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 sesuai dengan tujuan dan semangat undang-undang tersebut untuk melindungi pihak Indonesia dalam suatu perjanjian. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang mengatakan, barang siapa menandatangani dokumen dianggap mengerti dan setuju atas isinya.
Rumusan ini, apabila diterapkan secara konsisten oleh Pengadilan, diharapkan dapat melindungi pihak dalam perjanjian dari penyalahgunaan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 oleh debitor dalam perjanjian yang ingin menggunakan ketentuan ini sebagai sarana untuk keluar dari kewajibannya, padahal, merujuk pada Pasal 1331 KUHPerdata serta Schutznorm theorie, pelanggaran atas Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 ini tidak serta merta membuat perjanjian menjadi batal, namun hanya dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak Indonesia dalam perjanjian.
Iktikad Tidak Baik dalam Rumusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rumusan Mahkamah Agung di dalam SEMA 3/2023 di atas memberikan suatu penafsiran penerapan pasal yang menarik untuk dikaji, yaitu “…kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak”
Pada dasarnya, semua perjanjian di Indonesia wajib didasarkan pada iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menurut doktrin, hukum perdata Indonesia menganut doktrin contracto bona fides. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata harus ditafsirkan, bahwa pihak dalam membuat perjanjian harus berdasarkan niat yang jujur dan tulus. Hakim atas dasar Ps. 1338 ayat (3) KUHPerdata bisa merubah, memperluas atau menghapus kewajiban yang secara tegas ditetapkan dalam perjanjian, baik atas dasar keadaan yang ada pada saat perjanjian ditutup atau atas dasar keadaan yang timbul kemudian.
Lalu bagaimana menafsirkan itikad baik dalam perjanjian? Sayangnya sejauh penelitian penulis, masih belum ada keseragaman dari putusan Pengadilan mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik. Menurut Pitlo[1], bahwa memenuhi tuntutan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian sesuai dengan tuntutan kepantasan dan kepatutan. Oleh karena itu, adalah kewenangan hakim untuk melihat kepantasan dan kepatutan dalam suatu perjanjian.
Kepantasan dan kepatutan ini sangat bervariasi dan bergantung dari masing-masing perkara. Misalnya, dalam perkara jual beli tanah, SEMA No. 4 Tahun 2016 merumuskan itikad baik sebagai:
- Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)
- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.”
Kepantasan dan kepatutan ini sangat bervariasi dan bergantung dari masing-masing perkara. Misalnya, dalam perkara jual beli tanah, SEMA No. 4 Tahun 2016 merumuskan itikad baik sebagai:
Menyikapi Perkembangan Persyaratan Bahasa Indonesia
Meskipun patut untuk disambut baik dan memberikan dasar penafsiran dan pelaksanaan atas Ps. 31 UU No. 24/2009, namun perlu disadari SEMA ini hanya memberikan rumusan yang merupakan rujukan bagi para Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan demikian, SEMA ini bukanlah hukum yang mengikat seluruh masyarakat.
Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa kehati-hatian dalam membuat dan menyiapkan perjanjian sangat diperlukan. Sehingga, pembuatan kontrak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar khususnya perjanjian-perjanjianyang pihaknya adalah badan/warga negara Republik Indonesia patut untuk terus dilakukan. Setidaknya hingga ada Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan atas Ps. 31 UU No. 24/2009 yang menguatkan rumusan Mahkamah Agung ini.
[1] A. Pitlo, Het Verbintenissenrechtm naar het Nedelands Burgelijk Wetboek, hlm. 183.